 |
| Oleh: Rodifatun Annisa, Kader HMI Komisariat Cakraningrat |
Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Abraham Lincoln merumuskannya secara sederhana, government of the people, by the people, and for the people. Dalam konteks modern, demokrasi bukan hanya sekadar sistem politik, melainkan juga sebuah nilai yang menekankan partisipasi rakyat, persamaan hak, serta perlindungan kebebasan sipil. Namun, cita-cita demokrasi itu terasa jauh dari kenyataan. Ketika rakyat berteriak di jalan menuntut keadilan, wakil rakyat justru memilih bekerja dari rumah, seakan menjauh dari suara yang mestinya mereka dengar.
Gelombang demonstrasi kembali memenuhi jalan-jalan kota besar di Indonesia. Teriakan rakyat menggema, menyuarakan rasa kekecewaan atas ketidakadilan yang mereka rasakan. Namun, di saat yang sama, gedung parlemen yang seharusnya menjadi ruang paling ramai menyerap aspirasi rakyat justru terasa sunyi. Anggota DPR memilih bekerja dari rumah (WFH), bersembunyi di balik layar rapat virtual, jauh dari suara aspirasi rakyat yang mestinya mereka wakili. Fenomena ini bukan sekadar perbedaan tempat bekerja, tetapi mencerminkan jurang yang makin lebar antara rakyat dan wakil rakyatnya.
DPR adalah simbol
demokrasi, lembaga yang mengaku “rumah rakyat”. Namun bagaimana mungkin rumah
rakyat itu kosong, sementara rakyat justru berdesakan di jalan? WFH memang bisa
dibenarkan dalam kondisi tertentu, tetapi dalam konteks gelombang protes
nasional, kebijakan itu tampak seperti upaya menjauhkan diri dari suara publik.
Di jalan, rakyat berteriak menuntut keadilan mulai dari protes terhadap
kebijakan tunjangan DPR, kenaikan pajak, hingga kasus tragis yang merenggut
nyawa seorang anak muda di Jakarta. Namun di parlemen, rapat berlangsung kaku,
dingin, dan sunyi dari kehadiran rakyat.
Demokrasi dibangun
atas asas partisipasi rakyat. Ironisnya, rakyat yang berteriak justru
dihadapkan dengan gas air mata, sementara mereka yang duduk nyaman di kursi
parlemen memilih berjarak melalui layar tv dirumahnya. Inilah paradoks
demokrasi hari ini suara keras rakyat di jalan raya tidak bergema di ruang
sidang parlemen. Alih-alih menjadi penyalur aspirasi, DPR kerap terlihat
sebagai menara gading yang steril dari keluh kesah rakyat. Padahal, legitimasi
mereka lahir dari suara rakyat.
Fenomena DPR WFH di tengah protes rakyat menghadirkan pertanyaan mendasar untuk siapa mereka bekerja? Jika rakyat berteriak di jalan, mengapa wakil rakyat justru bersembunyi di balik layar rapat virtual? Dalam sistem demokrasi, parlemen bukan sekadar ruang perumusan undang-undang, melainkan juga ruang untuk mendengar. Ketika suara rakyat menggelegar di jalanan, justru di situlah anggota parlemen seharusnya hadir, bukan menghindar.
Tiga Hal yang Hilang dari DPR Hari Ini, atau bahkan memang sejak awal tidak ada;
- Keberanian Menyerap Aspirasi.
Fungsi utama DPR bukan sekadar membaca laporan media atau menerima dokumen resmi, melainkan hadir langsung dalam denyut aspirasi rakyat. Tanpa keberanian untuk turun mendengar suara di jalanan, perwakilan rakyat hanya menjadi simbol tanpa makna.
2. Integritas Moral dan Kepedulian Publik.
Pilihan DPR untuk bekerja dari rumah di tengah gelombang demonstrasi memperlihatkan jarak moral antara wakil rakyat dan rakyatnya. Kehadiran fisik di parlemen seharusnya bukan sekadar rutinitas, tetapi bentuk tanggung jawab moral bahwa penderitaan rakyat juga adalah penderitaan mereka.
3. Ruang Dialog yang Sehat.
Demokrasi hidup dari dialog, bukan dari kebungkaman. Sayangnya, ruang pertemuan antara DPR dan massa aksi hampir tidak pernah ada. Akibatnya, rakyat merasa dipinggirkan, sementara ketidakpercayaan terhadap lembaga perwakilan semakin dalam.
Dalam kondisi seperti ini, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral yang tidak bisa diabaikan. Sejarah mencatat, mahasiswa selalu menjadi suara alternatif ketika parlemen memilih bungkam. Dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi, mahasiswa turun ke jalan raya saat gedung parlemen lebih memilih sunyi. Mereka hadir sebagai pengingat bahwa kekuasaan sejati tetap berada di tangan rakyat, bukan di kursi parlemen yang sering kehilangan arah.
Namun, aksi hari ini tidak lagi hanya milik mahasiswa. Di jalan raya, teriakan juga datang dari pelajar SMA, pekerja, hingga kalangan masyarakat sipil lainnya. Kehadiran mereka menguatkan bahwa keresahan terhadap kondisi bangsa ini bukan hanya isu kampus atau gerakan elit intelektual, melainkan kegelisahan kolektif yang dirasakan semua lapisan masyarakat. Mahasiswa tetap menjadi motor penggerak, tetapi kini mereka bergerak bersama rakyat.
Keterlibatan pelajar SMA menjadi sinyal yang tidak bisa
diremehkan. Seharusnya, mereka fokus pada pendidikan dan masa depan, tetapi
justru terpanggil untuk ikut turun ke jalan. Hal ini menandakan bahwa krisis
demokrasi sudah menembus batas usia anak-anak muda yang masih duduk di bangku
sekolah pun merasakan dampaknya. Bila generasi muda seawal itu sudah merasa
perlu bersuara, maka ini bukti bahwa kegagalan parlemen telah menyentuh sampai
ke akar terdalam kehidupan berbangsa.
Mahasiswa dan pelajar SMA yang bergandengan dengan rakyat
luas menunjukkan wajah demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi bukan sekadar
prosedur pemilu lima tahun sekali atau rapat-rapat di gedung parlemen,
melainkan partisipasi aktif rakyat dalam mengawasi jalannya kekuasaan. Jalan
raya kini menjadi ruang politik alternatif ketika ruang formal ditutup rapat.
Teriakan mahasiswa, pelajar, dan rakyat di jalan raya adalah
alarm demokrasi yang tidak bisa diabaikan. Alarm itu memberi tanda bahwa sistem
perwakilan kita sedang sakit parah. DPR yang memilih bekerja dari rumah (WFH)
di tengah demonstrasi besar justru semakin memperkuat jarak antara rakyat dan
wakilnya. Keheningan parlemen hari ini adalah luka bagi demokrasi, sementara
teriakan di jalan adalah obat penawarnya.
Karena itu, DPR harus kembali mengingat esensi keberadaannya, mendengar rakyat, hadir bersama rakyat, dan berdialog dengan rakyat. Tanpa itu semua, parlemen hanya akan terus menjadi gedung sunyi yang kehilangan legitimasi. Dan pada akhirnya, sejarah akan mencatat bahwa suara sejati bangsa ini tidak pernah lahir dari gedung parlemen, melainkan dari jalan raya.
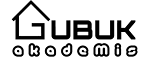







0 Komentar